Originally created by Fu
Rujuk merujuk pasien sudah barang tentu menjadi hal yang lumrah terjadi dalam mekanisme pelayanan kesehatan. Tentunya hal ini telah menjadi rutinitas yang dianggap "biasa" bahkan "seharusnya" dilakukan, bila memang suatu instansi pelayanan kesehatan tidak mampu menangani, hingga menyerahkannya pada instansi pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan dianggap "mampu" menangani. Namun, dibalik dianggap "biasa"-nya rutinitas ini, telah menjadi rahasia umum bahwa rujuk merujuk ini juga menyimpan sekelumit kisah sampai banyak kontroversi.
Sebagai salah satu pelayan kesehatan masyarakat, profesi saya tentunya ikut ambil bagian dalam lingkaran sistem rujukan ini. Apalagi profesi bidan ini ditentukan sebagai elemen dasar pelayan kesehatan pertama, yang menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dibidang kesehatan ibu dan anak tentunya. Suatu kehormatan sekaligus beban tersendiri sebenarnya bila mengingat akan kewajiban dan tuntutan yang harus dipenuhi.
Menjadi sebuah prestasi bila kasus normal dapat tertangani dengan baik, namun menjadi aib serta problema berkelanjutan bila ada kasus yang tak dapat tertangani. Hal tersebut disebabkan beragam kemungkinan mulai dari ketidakmampuan deteksi dini, ketidakpatuhan melakukan tindakan sesuai SOP, keterlambatan merujuk, dan berbagai alasan lain. Disinilah sebenarnya sistem kolaborasi itu berfungsi. Dimana harus ada kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan lain juga instansi pelayanan kesehatan lain. Pada kolaborasi rujukan berbagai kasus terkadang tak lepas dari ketidaksesuaian dan kesalahpahaman. Acap kali fenomena "saling menyalahkan" terjadi baik itu antara pasien dan petugas kesehatan maupun antar sesama petugas kesehatan itu sendiri.
Serba salah rasanya bila keputusan merujuk itu harus ditetapkan. Kesan ketidakmampuan dalam penanganan seringkali terlontar dari pihak pasien terhadap petugas kesehatan pertama yang menanganinya. Belum cukup sampai disitu, terkadang sindiran dan kesan “menyalahkan” oleh petugas kesehatan tempat rujukan kerap kali harus diterima oleh pihak yang merujuk pasien. Apalagi bila kegawatdaruratan obstetri dan neonatal itu menimbulkan sesuatu yang fatal. Faktanya memang instansi pelayanan kesehatan yang menyumbang AKI dan AKB paling tinggi adalah rumah sakit, dan sebagian besar penyebabnya didapat dari banyaknya kasus rujukan. Dan fenomena saling menyalahkan memang tak dapat dihindarkan, berlangsung sekaligus dengan tindakan saling menutupi kesalahan bila Audit Maternal Perinatal dilakukan.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, akan terjadi tuding menuding yang tidak akan pernah berujung sampai kapanpun. Petugas kesehatan tempat rujukan menyalahkan petugas yang merujuk, petugas yang merujuk angkat tangan menyalahkan pasien, pasien sendiri berkilah pada keterbatasan biaya dan pengetahuan atau bahkan kembali menyalahkan petugas yang merujuk. Tak akan berakhir karena membentuk lingkaran bahkan siklus tak berkesudahan yang itu-itu saja.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, pasien sebagai rakyat biasa sebenarnya bisa menuntut bidan atau petugas kesehatan lain atas MAL praktek di saat kegawatdaruratan terjadi. Karena faktanya, memang masih ada saja petugas kesehatan yang memanfaatkan "kebodohan" pasien akan hal medis sebagai alas melindungi diri dari ketidaksesuaian hukum dan etika profesi. Pasien juga tak bisa disalahkan sepenuhnya saat ia lebih memilih ahli pengobatan alternatif, paraji, atau bahkan dukun untuk kesembuhannya. Karena faktanya, biaya kesehatan di negara ini dianggap sudah mulai tidak masuk akal lagi.
Ironis memang, karena sering kali keharusan malah berbanding terbalik dengan kemampuan. Seperti dalam hal bersalin misalnya, masyarakat "menengah ke bawah" mati-matian berusaha ingin bisa melahirkan normal karena ketidakmampuan biaya operasi, sementara di sisi lain masyarakat "menengah ke atas" malah bersikeras ingin operasi caesar padahal masih bisa melahirkan normal. Di lain hal, saat petugas instansi pelayanan kesehatan pemerintah bekerja keras menangani pasien yang melebihi daya tampung, banyak" instansi swasta malah bersikukuh mengutamakan kepuasan pelanggan yang ditebus sesuai dengan perlembar materi yang tersanggupi.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, petugas kesehatan sebagai abdi negara wajar menuntut akan ketidaksejahteraan dirinya. Karena bagaimanapun tenaga dan jasa harus berbanding lurus pada penghargaan yang didapat. Dimana tuntutan akan "target pencapaian" dan “berkas pelaporan” yang menumpuk, tumpang tindih dengan keharusan terlaksananya pelayanan yang memuaskan sekaligus. Sementara itu, harga yang didapat tidaklah sebanding dengan kerja yang dilakukan. Ditambah lagi aturan perundang-undangan yang dibuat se-"ideal" mungkin nyatanya tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebenarnya. Seperti halnya permenkes terbaru tentang wewenang praktek bidan misalnya, di sana tertuang beberapa aturan yang terkesan "maksa" tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. Bagaimana tidak, bila beberapa wewenang bidan akhirnya dibatasi dengan dilatarbelakangi berbagai kasus melenceng yang terlapor dilakukan bidan. Aneh memang bila pembuat kebijakan tidaklah termasuk profesi yang menjalankan kebijakan itu sendiri, karena buktinya tidak ada seorang pun "bidan" yang menjadi bagian dari pembuat kebijakan tersebut. Sementara di sisi lain program yang masih diusahakan adalah "bidan desa", tidak diimbangi oleh keberadaan “obgyn desa” misalnya. Jadi pantaslah bila kasus kegawatdaruratan yang seringkali terjadi di daerah terpencil, masih menyumbang AKI dan AKB dikarenakan ketidakterjangkauan tempat pelayanan kesehatan juga ketidakmampuan petugas dalam penanganan.
Ironis memang, karena seringkali ketidaksesuaian terbantah oleh kelumrahan. Tidaklah heran bila ekspresi datar bahkan tidak mengenakkan muncul dari petugas kesehatan dalam menyaksikan kegawatdaruratan bahkan kematian. Meskipun hal itu telah menjadi "kewajaran", tetapi sebenarnya hal tersebut menjadi ketakutan dan kegetiran tersendiri bagi mereka. Karena bila tidak dengan sikap seperti itu, siapa lagi yang rela hati menangani pasien dengan sekejap melupakan materi, ditengah tekanan akan tuntutan profesi dan penghidupan sekaligus.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, pemerintah mungkin menjadi pangkal dari segala problematika ini. Segala aspek di luar kesehatan pun pastilah menuduh tersangka utama dari berbagai tumpahan kesalahan itu adalah pemerintah. Disamping berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan memunculkan banyaknya program kesehatan, entah itu mulai dari jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, pemerataan tenaga kesehatan, pengadaan tunjangan kesehatan, dan berbagai program serta kebijakan lain. Namun hal itu tidak lantas menjadikan derajat kesehatan bangsa ini segera membaik, atau setidaknya bisa disejajarkan dengan negara-negara tetangga terdekat minimalnya. Selain itu, hal tersebut juga tak membuat status korupsi bidang kesehatan yang ada di peringkat ketiga (setelah pendidikan dan agama) menjadi menurun jua.
Ironis memang, di saat upaya perbaikan yang diimpikan tak bisa lepas dari ketidaksesuaian tindakan nyata. Dimana kita tak bisa menutup mata bahwa pelayanan yang berkualitas harus didukung pula oleh petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Untuk memenuhi itu semua, diperlukan dana yang tidak sedikit tentunya. Ya, bagaimanapun semuanya berujung pada ketersediaan biaya. Parahnya lagi, bukanlah karena pengadaan obat atau alat kesehatan yang harganya mahal semua ini terhambat, tapi justru proses pengadaan turunnya dana yang biasanya terlipat di berbagai tingkat.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, semuanya tidak bisa dinyatakan mutlak bersalah atau tidak bersalah. Namun satu hal yang pasti, bahwa semuanya ikut bertanggungjawab dalam kelancaran pelayanan kesehatan, baik itu masyarakat, petugas kesehatan, juga pemerintah. Tidaklah hanya cukup puas dengan pencapaian 380/100.000 pada AKI dan 29/1000 pada AKB (Data tahun 2010). Meskipun faktanya memang terjadi penurunan per tahunnya, tapi seharusnya kegagalan visi Indonesia Sehat 2010 menjadi tamparan yang cukup dahsyat, sebagai bahan refleksi dan introspeksi seluruh elemen kesehatan di negara ini. Ya, setidaknya target MDG’s masih 4 tahun lagi kan?
Seharusnya kita semua tak perlu lagi berkutat pada pertanyaan "Siapa yang salah?". Lebih baik beralih pada pertanyaan "Siapa yang bergerak memperbaiki?".
Kalau bukan kita, siapa lagi?
*ah fu, kau masih kecil, beraninya kau bicara!
1 April 2011
Rujuk merujuk pasien sudah barang tentu menjadi hal yang lumrah terjadi dalam mekanisme pelayanan kesehatan. Tentunya hal ini telah menjadi rutinitas yang dianggap "biasa" bahkan "seharusnya" dilakukan, bila memang suatu instansi pelayanan kesehatan tidak mampu menangani, hingga menyerahkannya pada instansi pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan dianggap "mampu" menangani. Namun, dibalik dianggap "biasa"-nya rutinitas ini, telah menjadi rahasia umum bahwa rujuk merujuk ini juga menyimpan sekelumit kisah sampai banyak kontroversi.
Sebagai salah satu pelayan kesehatan masyarakat, profesi saya tentunya ikut ambil bagian dalam lingkaran sistem rujukan ini. Apalagi profesi bidan ini ditentukan sebagai elemen dasar pelayan kesehatan pertama, yang menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dibidang kesehatan ibu dan anak tentunya. Suatu kehormatan sekaligus beban tersendiri sebenarnya bila mengingat akan kewajiban dan tuntutan yang harus dipenuhi.
Menjadi sebuah prestasi bila kasus normal dapat tertangani dengan baik, namun menjadi aib serta problema berkelanjutan bila ada kasus yang tak dapat tertangani. Hal tersebut disebabkan beragam kemungkinan mulai dari ketidakmampuan deteksi dini, ketidakpatuhan melakukan tindakan sesuai SOP, keterlambatan merujuk, dan berbagai alasan lain. Disinilah sebenarnya sistem kolaborasi itu berfungsi. Dimana harus ada kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan lain juga instansi pelayanan kesehatan lain. Pada kolaborasi rujukan berbagai kasus terkadang tak lepas dari ketidaksesuaian dan kesalahpahaman. Acap kali fenomena "saling menyalahkan" terjadi baik itu antara pasien dan petugas kesehatan maupun antar sesama petugas kesehatan itu sendiri.
Serba salah rasanya bila keputusan merujuk itu harus ditetapkan. Kesan ketidakmampuan dalam penanganan seringkali terlontar dari pihak pasien terhadap petugas kesehatan pertama yang menanganinya. Belum cukup sampai disitu, terkadang sindiran dan kesan “menyalahkan” oleh petugas kesehatan tempat rujukan kerap kali harus diterima oleh pihak yang merujuk pasien. Apalagi bila kegawatdaruratan obstetri dan neonatal itu menimbulkan sesuatu yang fatal. Faktanya memang instansi pelayanan kesehatan yang menyumbang AKI dan AKB paling tinggi adalah rumah sakit, dan sebagian besar penyebabnya didapat dari banyaknya kasus rujukan. Dan fenomena saling menyalahkan memang tak dapat dihindarkan, berlangsung sekaligus dengan tindakan saling menutupi kesalahan bila Audit Maternal Perinatal dilakukan.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, akan terjadi tuding menuding yang tidak akan pernah berujung sampai kapanpun. Petugas kesehatan tempat rujukan menyalahkan petugas yang merujuk, petugas yang merujuk angkat tangan menyalahkan pasien, pasien sendiri berkilah pada keterbatasan biaya dan pengetahuan atau bahkan kembali menyalahkan petugas yang merujuk. Tak akan berakhir karena membentuk lingkaran bahkan siklus tak berkesudahan yang itu-itu saja.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, pasien sebagai rakyat biasa sebenarnya bisa menuntut bidan atau petugas kesehatan lain atas MAL praktek di saat kegawatdaruratan terjadi. Karena faktanya, memang masih ada saja petugas kesehatan yang memanfaatkan "kebodohan" pasien akan hal medis sebagai alas melindungi diri dari ketidaksesuaian hukum dan etika profesi. Pasien juga tak bisa disalahkan sepenuhnya saat ia lebih memilih ahli pengobatan alternatif, paraji, atau bahkan dukun untuk kesembuhannya. Karena faktanya, biaya kesehatan di negara ini dianggap sudah mulai tidak masuk akal lagi.
Ironis memang, karena sering kali keharusan malah berbanding terbalik dengan kemampuan. Seperti dalam hal bersalin misalnya, masyarakat "menengah ke bawah" mati-matian berusaha ingin bisa melahirkan normal karena ketidakmampuan biaya operasi, sementara di sisi lain masyarakat "menengah ke atas" malah bersikeras ingin operasi caesar padahal masih bisa melahirkan normal. Di lain hal, saat petugas instansi pelayanan kesehatan pemerintah bekerja keras menangani pasien yang melebihi daya tampung, banyak" instansi swasta malah bersikukuh mengutamakan kepuasan pelanggan yang ditebus sesuai dengan perlembar materi yang tersanggupi.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, petugas kesehatan sebagai abdi negara wajar menuntut akan ketidaksejahteraan dirinya. Karena bagaimanapun tenaga dan jasa harus berbanding lurus pada penghargaan yang didapat. Dimana tuntutan akan "target pencapaian" dan “berkas pelaporan” yang menumpuk, tumpang tindih dengan keharusan terlaksananya pelayanan yang memuaskan sekaligus. Sementara itu, harga yang didapat tidaklah sebanding dengan kerja yang dilakukan. Ditambah lagi aturan perundang-undangan yang dibuat se-"ideal" mungkin nyatanya tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebenarnya. Seperti halnya permenkes terbaru tentang wewenang praktek bidan misalnya, di sana tertuang beberapa aturan yang terkesan "maksa" tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. Bagaimana tidak, bila beberapa wewenang bidan akhirnya dibatasi dengan dilatarbelakangi berbagai kasus melenceng yang terlapor dilakukan bidan. Aneh memang bila pembuat kebijakan tidaklah termasuk profesi yang menjalankan kebijakan itu sendiri, karena buktinya tidak ada seorang pun "bidan" yang menjadi bagian dari pembuat kebijakan tersebut. Sementara di sisi lain program yang masih diusahakan adalah "bidan desa", tidak diimbangi oleh keberadaan “obgyn desa” misalnya. Jadi pantaslah bila kasus kegawatdaruratan yang seringkali terjadi di daerah terpencil, masih menyumbang AKI dan AKB dikarenakan ketidakterjangkauan tempat pelayanan kesehatan juga ketidakmampuan petugas dalam penanganan.
Ironis memang, karena seringkali ketidaksesuaian terbantah oleh kelumrahan. Tidaklah heran bila ekspresi datar bahkan tidak mengenakkan muncul dari petugas kesehatan dalam menyaksikan kegawatdaruratan bahkan kematian. Meskipun hal itu telah menjadi "kewajaran", tetapi sebenarnya hal tersebut menjadi ketakutan dan kegetiran tersendiri bagi mereka. Karena bila tidak dengan sikap seperti itu, siapa lagi yang rela hati menangani pasien dengan sekejap melupakan materi, ditengah tekanan akan tuntutan profesi dan penghidupan sekaligus.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, pemerintah mungkin menjadi pangkal dari segala problematika ini. Segala aspek di luar kesehatan pun pastilah menuduh tersangka utama dari berbagai tumpahan kesalahan itu adalah pemerintah. Disamping berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan memunculkan banyaknya program kesehatan, entah itu mulai dari jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, pemerataan tenaga kesehatan, pengadaan tunjangan kesehatan, dan berbagai program serta kebijakan lain. Namun hal itu tidak lantas menjadikan derajat kesehatan bangsa ini segera membaik, atau setidaknya bisa disejajarkan dengan negara-negara tetangga terdekat minimalnya. Selain itu, hal tersebut juga tak membuat status korupsi bidang kesehatan yang ada di peringkat ketiga (setelah pendidikan dan agama) menjadi menurun jua.
Ironis memang, di saat upaya perbaikan yang diimpikan tak bisa lepas dari ketidaksesuaian tindakan nyata. Dimana kita tak bisa menutup mata bahwa pelayanan yang berkualitas harus didukung pula oleh petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Untuk memenuhi itu semua, diperlukan dana yang tidak sedikit tentunya. Ya, bagaimanapun semuanya berujung pada ketersediaan biaya. Parahnya lagi, bukanlah karena pengadaan obat atau alat kesehatan yang harganya mahal semua ini terhambat, tapi justru proses pengadaan turunnya dana yang biasanya terlipat di berbagai tingkat.
Kalau terus bertanya siapa yang salah, semuanya tidak bisa dinyatakan mutlak bersalah atau tidak bersalah. Namun satu hal yang pasti, bahwa semuanya ikut bertanggungjawab dalam kelancaran pelayanan kesehatan, baik itu masyarakat, petugas kesehatan, juga pemerintah. Tidaklah hanya cukup puas dengan pencapaian 380/100.000 pada AKI dan 29/1000 pada AKB (Data tahun 2010). Meskipun faktanya memang terjadi penurunan per tahunnya, tapi seharusnya kegagalan visi Indonesia Sehat 2010 menjadi tamparan yang cukup dahsyat, sebagai bahan refleksi dan introspeksi seluruh elemen kesehatan di negara ini. Ya, setidaknya target MDG’s masih 4 tahun lagi kan?
Seharusnya kita semua tak perlu lagi berkutat pada pertanyaan "Siapa yang salah?". Lebih baik beralih pada pertanyaan "Siapa yang bergerak memperbaiki?".
Kalau bukan kita, siapa lagi?
*ah fu, kau masih kecil, beraninya kau bicara!
1 April 2011





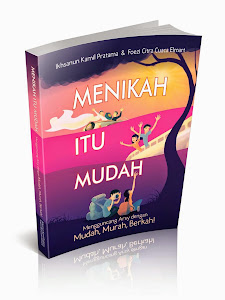









0 komentar:
Posting Komentar